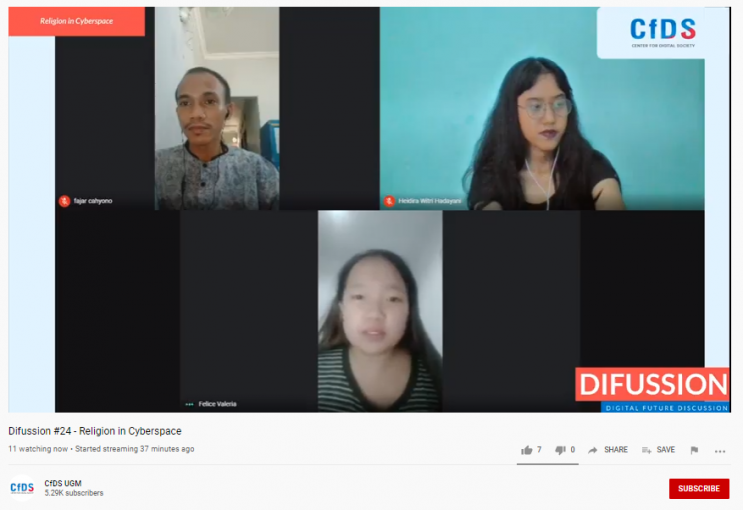
Yogyakarta, 16 Mei 2020—Digital Future Discussion oleh Center for Digital Society (CfDS) #24 yang menghadirkan dua pembicara dari Research Assistant CfDS (15/05). Salah satu pembicara, Heidira Hadayani, menyebutkan bahwa tidak selamanya teknologi digial bertolak belakang dengan nilai-nilai agama dan justru bisa dimanfaatkan untuk kepentingan agama itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari praktiknya di Singapura yang masyarakatnya sangat awam dengan teknologi tetapi tingkat religiositasnya tetap tinggi.
Keberadaan teknologi digital sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, teknologi digital ternyata juga bermanfaat bagi keagamaan, misalnya untuk menyebarkan pesan religius dan ajaran agama. Beriringan dengan manfaat tersebut, tentunya ada beberapa risiko yang harus diantisipasi, yaitu berkembangnya paham radikal dan ekstrimisme.
“Teknologi digital justru bisa meningkatkan peran pemuka agama dalam kehidupan masyarakat,” kata Heidira. Para pemuka agama bisa memanfaatkan media sosial untuk menjangkau para jamaah dan menyebarkan informasi keagamaan. Selain media sosial, website dan email bisa digunakan untuk membagikan pesan serta teks-teks religius lainnya tanpa harus bertemu langsung.
Tidak hanya itu, teknologi digital juga memengaruhi cara pandang seseorang dalam memaknai suatu agama atau keyakinan. Prosesnya dimulai ketika seseorang bertemu banyak orang dengan keyakinan yang sama dan merasa menjadi bagian dari mereka (sense of belonging). Hal ini akan membantu memenuhi kebutuhan spiritualnya hingga akhirnya membentuk persepsi di pikiran mereka tentang agama itu.
Selain itu, Heidira juga menyebutkan bahwa dunia digital menjadi tempat berkembangnya keyakinan-keyakinan minoritas yang tertekan atau ditentang di kehidupan nyata. Salah satu contohnya adalah kelompok Muslim Syiah yang tercatat memiliki 23 medium untuk membangun komunitasnya di dunia digital. Karena keberadaannya yang dilarang dan terstigma negatif, kelompok Muslim Syiah memanfaatkan dunia siber untuk merekrut anggota dan menyebarkan ajarannya. Akan tetapi, Heidira juga menjelaskan bahwa masih ada ketimpangan kekuasaan antara kelompok mayoritas dan minoritas di dunia digital. Tekanan pengawasan pemerintah menjadi salah satu ancaman bagi kelompok minoritas.
Heidira mengaku optimis bahwa teknologi digital bisa bermanfaat untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama. Melalui dunia digital, seseorang bisa mendapat persepsi baru bahwa keyakinan yang ada tidak sebatas agama-agama yang diakui oleh masyarakat di dunia nyata saja.
“Namun, menilai apakah ini lebih berdampak positif atau negatif itu cukup kompleks. Teknologi digital mampu mendorong terbukanya ruang publik dalam keagamaan. Akan tetapi, teknologi digital juga mampu menyuburkan paham-paham radikalisme yang berbahaya,” imbuh Heidira.
Sependapat dengan Heidira, Felice Valeria selaku pembicara kedua menyampaikan bahwa teknologi digital mendorong munculnya berbagai radikalisasi daring atau berkembangnya paham ekstrim. Paham-paham radikal mudah berkembang di media sosial atau dunia digital karena gratis, mudah digunakan, berlaku dengan sistem anonimitas, serta adanya kecenderungan echo chamber yang memudahkan mereka untuk menggaungkan ide-ide yang mereka yakini.
Pada umumnya, paham radikalisme dan ekstrimisme ini dibagi menjadi kekerasan dan non-kekerasan. Menurut Felice, paham-paham radikal dengan unsur kekerasan ini lah yang berbahaya. Contohnya kasus pada tahun 2019 ketika seorang teroris melakukan penembakan terhadap beberapa jamaah masjid di Selandia Baru dan menyiarkannya langsung di Facebook. Kasus ini merupakan salah satu bentuk radikalisme di dunia digital dengan kekerasan yang tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga bisa menebar ancaman.
Oleh karena itu, Felicia menyebut bahwa pemerintah dan perusahaan media sosial memiliki peran yang besar untuk mencegah berkembangnya paham radikal tersebut, misalnya dengan sensor atau take down. Akan tetapi, tindakan sensor atau take down itu harus didasari oleh justifikasi yang jelas. Hal ini penting untuk menjamin kebebasan berpendapat di negara demokrasi.
“Selain itu, para pemuka agama juga bisa mengupayakan narasi-narasi yang tidak kalah menarik untuk mempertahankan keyakinan masyarakat dari paham radikal. Jangan sampai kalah dengan narasi yang diciptakan para teroris di media sosial,” kata Felicia. Harapannya, hal ini dapat mencegah berkembangnya radikalisme di dunia digital dan mewujudkan ruang publik keagamaan yang aman bagi penggunanya. (/Raf)
