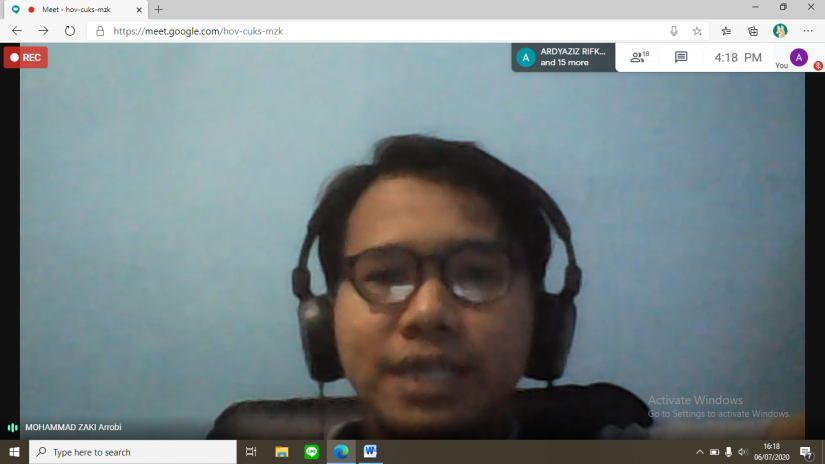
Yogyakarta, 6 Juli 2020—Jamaah Muslim Fisipol (JMF) kembali menyelenggarakan diskusi Ngobrol Perkara Ilmu (NGOPI) bertajuk “Panjang Penyelesaian Rasisme Papua: Apa yang masih kurang?” bersama Zaki Arrobi selaku Dosen Departemen Sosiologi pada Senin silam melalui Google Meet.
Zaki membuka diskusi dengan membahas bagaimana upaya Islam melawan rasisme melalui pesannya yang sangat universal. “Berbagai perisiwa historis pada masa awal Islam menunjukan banyak budak berkulit hitam yang dibebaskan oleh para sahabat nabi, yaitu assabiqunal awwalun. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa Agama Islam dapat menyebar secara luas karena egalitarianismenya,” ujar Zaki.
Namun sayangnya, rasisme masih berlangsung hingga saat ini. “Pertalian antara rasisme, kolonialisme dan kapitalisme tidak bisa dilepaskan. Kolonialisme pada awalnya didorong oleh rasa superioritas. Pada awalnya banyak yang menganggap kolonialisme adalah kultur, yakni seolah yakin bahwa orang kulit putih ditakdirkan untuk menjadi civilizer, yaitu agen yang memperadabkan bangsa lain. Hal inilah yang disebut oleh Foucault sebagai biopolitik dimana tubuh menjadi arena pertarungan politik. Didefinisikanlah kulit hitam dan putih serta antara yang civilized dan savage,” jelas Zaki.
Zaki menuturkan bahwa peristiwa wafatnya George Floyd— seorang waga kulit hitam di Amerika karena penyiksaan oleh aparat— menggambarkan adanya rasisme sistemik dan struktural. Di sistem pengadilan kriminal Amerika, terdapat survei yang menunjukan tahanan dengan orang kulit berwarna melebihi proporsi populasi secara kesuluruhan. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan banyaknya orang kulit hitam dengan pengahasilan rendah yang berpengaruh pada urusan ketidaklayakan perumahan serta pekerjaan informal.
Selanjutnya ketika melihat konteks rasisme di tingkat nasional yaitu Papua, Zaki menjelaskan bahwa penting untuk memahami kondisi rasisme Papua secara historis dan struktural. Zaki memetakan bahwa sumber konfiik di Papua terdiri atas masalah historis dan identitas politik, gagalnya pembangunan, marjinalisasi dan diskrminasi serta kekerasan negara di masa lalu.
“Ada stereotip yang sering melekat pada Orang Papus seperti pemalas, pemabuk dan lainnya. Stereotip tersebutlah yang menjadi bahan bakar persekusi masal seperti insiden Surabaya beberapa waktu lalu. Dan ketika mereka menyuarakan hak politiknya, seringkali mereka dianggap sebagai ancaman dibawah slogan “NKRI Harga Mati” yang saat ini bukan hanya milik tentara, tapi juga sudah merembes ke masyarakat sipil seperti ormas paramiliter,” ujar Zaki.
Menurut Zaki, hal tersebut disebut sebagai sekuritisasi dimana persoalan Papua secara dominan didekati dengan perspektif pertahanan dan kemanan. “Hak sipil untuk berorganisasi sangat terbatas, jurnalis dan media juga sangat dibatasi. Sangat disayangkan gerakan ini malah didekati dengan banyaknya personel aparat kemanan bukannya dengan melihat masalah rasisme secara struktural dan komperhensif,” jelas Zaki.
“Penyelesaian masalah rasisme Orang Papua dan di Papua melalui pendekatan pembangunan telah gagal. Berbagai pembangunan fisik seperti jembatan, jalan, dan Trans Papua ternyata tidak meredakan ketegangan sosial di ranah grassroots. Justru pembangunan infrastuktur malah meninggalkan masyarakat asli Papua itu sendiri, meminggirkan komunitas adat,” ujar Zaki.
“Pendekatan keamanan pun juga telah gagal dan malah menyisakan luka, problem penuntasan HAM harus diselesaikan terlebih dahulu, akan sulit kalau hanya mengandalkan prioritas ekonomi. Ibaratnya, luka harus diobati dulu,” tambah Zaki.
Diakhir diskusi, Zaki menekankan pentingnya egalitarianisme bagi Papua. “Generasi baru harus bisa mengimajinasikan Papua yang lebih egaliter. Kita bisa belajar dari negara lain agar suatu kelompok yang mengalami diskriminasi rasial dan struktural bisa setara di masa mendatang,” ucap Zaki sekaligus menutup diskusi sore hari tersebut. (/Afn)
