
Yogyakarta, 17 Juli 2020—Center for Digital Society Fisipol UGM kembali hadir dengan Digital Future Discussion yang ke-28. Pada pertemuan Difussion kali ini, dua asisten riset CfDS, Jasmine Noor Andretha Putri dan Irnasya Shafira selaku pembicara membawakan topik seputar Social Justice in The Digital Age. Topik tersebut diangkat dalam rangka memperingati Hari Keadilan Internasional yang jatuh bertepatan dengan pelaksanaan acara, 17 Juli. Fajar Cahyono, asisten riset CfDS lainnya, juga turut memandu Difussion kali ini sebagai moderator.
Kedua materi yang dibawakan oleh Jasmine dan Ines diambil dari rubrik commentary CfDS yang mereka tulis. Jasmine membawakan materi tentang pergerakan anak muda melalui media sosial, khususnya para pengguna TikTok dan penggemar K-pop. Dalam materi ini, Jasmine mengambil studi kasus ‘prank’ pada Donald Trump dan kampanye Black Lives Matter yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut.
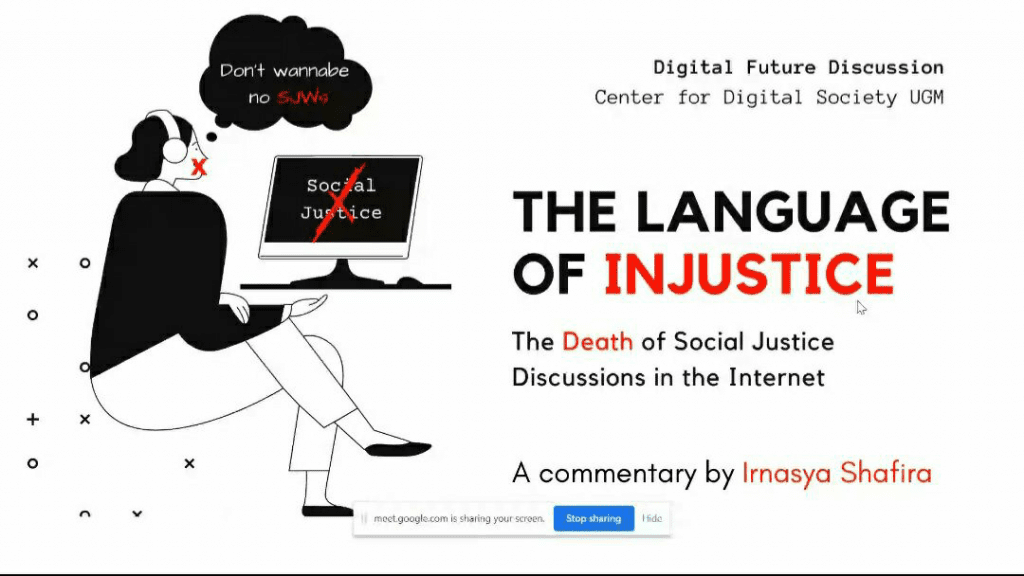
Sebelum membahas kedua kasus secara lebih rinci, Jasmine memulai pemaparan materinya dengan menjelaskan gambaran umum mengenai aktivisme kaum muda di era digital. Kasus ‘prank’ Trump terjadi pada momentum kampanye perdana Donald Trump setelah hiatus sementara karena COVID-19. Reservasi dari kampanye ini mencapai satu juta tiket. Namun, pada hari pelaksanaannya, hanya 6.200 orang yang datang ke lokasi kampanye. Jumlah yang timpang ini disebabkan banyaknya ajakan untuk melakukan reservasi “palsu”.
Berawal dari TikTok, khususnya sub-genre Alt TikTok, kemudian ajakan ini turut disebarkan melalui Twitter yang menyebabkan meningkatnya jumlah massa. Pergerakan massa melalui media sosial seperti ini juga terjadi dalam kampanye Black Lives Matter oleh para penggemar K-pop. Mulai dari melakukan spam video di tagar yang melawan gerakan Black Lives Matter, merusak sementara aplikasi Kepolisian Dallas karena spam video yang serupa, dan mengumpulkan donasi untuk kampanye BLM hingga jutaan dolar.
Jasmine menjelaskan, dua kasus ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan media sosial sebagai alternatif untuk aktivisme sosial. Selain itu, dua kasus tadi juga mengindikasikan bahwa perubahan politik bisa didorong melalui mekanisme sosio-kultural, tidak hanya melalui institusi politik konvensional. Institusi politik konvensional yang kompleks dan lama untuk menyesuaikan dengan perubahan baru mendorong penggunaan media sosial sebagai alat perubahan. Namun, bukan berarti fenomena ini menghilangkan politik partisipatoris konvensional, tetapi lebih menjadi diversifikasi metode ekspresi politik yang digunakan oleh kaum muda.
Sedikit berbeda dengan Jasmine, Ines lebih membahas mengenai bahasa ketidakadilan yang membunuh diskusi-diskusi keadilan sosial di internet. Mengawali materinya, Ines mengajak para peserta untuk bermain game sederhana. Pada game ini, Ines memberikan beberapa ciri-ciri yang merujuk pada stereotip ‘SJW’ di masyarakat. SJW atau social justice warrior adalah istilah derogatif untuk orang-orang yang memiliki pandangan sosial progresif, seperti pandangan feminisme, hak sipil, dan multikulturalisme.
Ines kemudian menceritakan sejarah perubahan makna SJW yang tadinya netral dan cenderung memuji justru menjadi negatif. Istilah SJW pertama kali muncul pada tahun 1991, ketika Montreal Gazette mendefinisikan seorang aktivis di Kanada. Penggunaan makna derogatif SJW secara publik baru terjadi pada tahun 2014, ketika terjadi skandal #GamerGate. Skandal ini memakan banyak korban, mulai dari ancaman pembunuhan dan pemerkosaan, hingga penyebaran data pribadi sang korban.
Istilah SJW kemudian disematkan oleh para pelaku dalam skandal ini pada orang-orang yang membela korban. Mereka merasa, seharusnya isu-isu kesejahteraan tidak diangkat di platform-platform umum. Perubahan konotasi makna SJW ini kemudian memunculkan bahasa ketidakadilan, yaitu istilah-istilah yang membisukan isu-isu ketidakadilan sosial yang perlu dibahas. Ines pun memberikan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggapi fenomena ini, seperti berhenti menggunakan bahasa ketidakadilan dan mulai berani menyuarakan keadilan.
Baik Jasmine maupun Ines menutup pemaparan materi mereka dengan sebuah quotes. Dalam memaparkan materi, tidak lupa keduanya mencantumkan unggahan-unggahan di media sosial sebagai contoh agar para peserta diskusi lebih memahami konteks yang dibicarakan. Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dibuka sebanyak tiga termin, dengan total delapan pertanyaan. Setelah foto bersama, kedua pembicara dipersilakan oleh moderator untuk menyampaikan pernyataan penutup.
“Bahasa ketidakadilan itu ada banyak bentuknya, bahkan hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Ayo sadari lagi, apakah pendapat kita membisukan suara orang lain? Jika iya, lebih baik tidak usah diunggah,” Pesan Ines. Jasmine menambahkan, “Kita sebagai kaum muda punya suara yang dapat digunakan untuk perubahan-perubahan yang lebih baik. Gunakan lah media sosial untuk menyuarakan itu.”
“Keadilan harus ditegakkan, keadilan harga mati,” ucap Fajar menutup diskusi pada pukul 16.31 WIB. Bagi yang tidak sempat bergabung, tayangan ulang dari Difussion ke-28 dapat ditonton di kanal Youtube CfDS. (/hfz)
