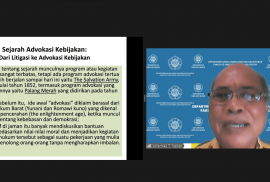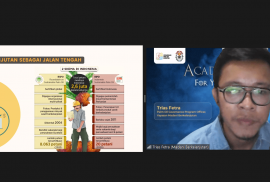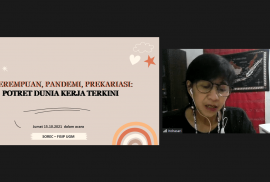Yogyakarta, 25 Oktober 2021─Departemen Politik Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, dan UGM Press menyelenggarakan webinar bedah buku ‘Tentang Kuasa’. Acara ini diselenggarakan secara daring dengan menghadirkan empat pembicara yang merupakan dosen DPP Fisipol UGM yaitu Dr. Wawan Mas’udi, Dr. Evi L Sutrisno, Dr. Amalinda Savirani, dan Dr. Joash Tapiheru. Pada kesempatan kali ini, acara dimoderatori oleh Desi Rahmawati selaku Peneliti Polgov Fisipol UGM dan diikuti oleh 250 peserta. Acara ini membahas berbagai topik penting dalam buku tentang kuasa mulai dari lingkup kajian dalam studi ilmu pemerintahan, hingga berbagai metodologi, dan pengajaran dalam ilmu politik pemerintahan.
Berita
Yogyakarta, 23 Oktober 2021─Dies Natalis FISIPOL UGM bukan hanya menjadi perayaan yang eksklusif hanya untuk sivitas akademika saat ini saja. Lebih dari itu, FISIPOL UGM juga mengajak para alumni lintas angkatan untuk turut merayakan Dies Natalis secara daring dalam acara Temu Alumni FISIPOL yang diselenggarakan pada Sabtu (23/10). Mengusung “Makna Sepanjang Masa” sebagai tajuknya, pada momen ini FISIPOL yang dipandu oleh Deby dan Faren selaku pembawa acara mengajak para alumni untuk nostalgia bersama dalam rangkaian kegiatan virtual gathering.
Yogyakarta, 22 Oktober 2021─DEMA FISIPOL UGM menyelenggarakan Kelas Riset X Big Data tentang Visualisasi Big Data melalui Zoom Meeting pada Jumat (22/10). Pembicara dalam acara kali ini adalah Wegik Prasetyo dan Vendi A. Nugroho selaku peneliti Big Data Polgov. Acara dimulai pada pukul 19.00 WIB dengan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dan umum.
Mengawali diskusi, Wegik menjelaskan mengenai alur riset big data yakni penemuan problem statement, dilanjutkan dengan research question yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci penelitian, data resource selection, crawling, processing, dan visualization. Dalam penyajian data, visualisasi sangat penting sebagai representasi data untuk memudahkan pembaca memahami data. Beberapa macam visualisasi data adalah visualisasi teks, visualisasi tabel, dan visualisasi grafik yang terdiri dari elemen titik, garis, dan batang. Vendi menjelaskan, teks biasa digunakan untuk menjelaskan 1 atau 2 angka, sedangkan tabel dan grafik cocok untuk menjelaskan banyak angka.
Yogyakarta, 22 Oktober 2021─Departemen Sosiologi FISIPOL UGM melalui Social Research Center atau SOREC berkolaborasi dengan Program Studi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan diskusi buku pada hari Jumat (22/10). Sesuai dengan tajuknya, yaitu “Jalan Menuju Utopia: Juliet B. Schor tentang Konsumerisme, Kemakmuran Sejati, dan Gaya Hidup Berkelanjutan”, Prof Dr. Heru Nugroho━Profesor di Departemen Sosiologi, FISIPOL UGM dengan minat kajian pada Teori Kritik, Sosiologi Ekonomi, dan Kritik Sosial Teknologi━membahas salah satu tulisan dalam buku “Melintas Batas” yang diterbitkan oleh (KBM) mengenai pandangan Juliet B. Schor tentang konsumerisme, kemakmuran sejati, dan gaya hidup berkelanjutan.
Yogyakarta, 22 Oktober 2021─FISIPOL Crisis Center atau FCC secara rutin mengadakan webinar series dalam rangka menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasinya selaku unit pencegahan pelecehan seksual di kalangan sivitas akademika FISIPOL UGM. Pada webinar series kelima yang diselenggarakan pada hari Jumat (22/10), FCC bekerja sama dengan Keluarga Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau KAPSTRA FISIPOL UGM, mengangkat tajuk “RUU PKS, Riwayatmu Kini: Polemik Komitmen Negara dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia” untuk melihat perjalanan panjang RUU PKS sebagai instrumen hukum yang memihak penyintas kasus kekerasan seksual di Indonesia.
Yogyakarta, 22 Oktober 2021─Departemen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, bersama dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital dan Mojok, turut memeriahkan salah satu rangkaian kegiatan yang diadakan PT KANISIUS pada hari Jumat (22/10), menjelang satu abad kontribusinya dalam berkarya di ranah penerbitan dan percetakan Indonesia. Kegiatan berupa bincang interaktif yang mengangkat tajuk “Literasi dan Falasi dalam Konten Digital” ini menghadirkan tiga narasumber yang sudah lama bergelut di bidang media, termasuk media digital, untuk memberikan ‘bekal’ kecakapan non-teknis dalam perancangan konten yang bernilai serta bermakna bagi para konten kreator.
Yogyakarta, 21 Oktober 2021─Center for Digital Society (CfDS) menghelat talkshow Digital Expert Talks #4 bersama Facebook Indonesia bertajuk “RUU PDP dan Perekonomian Digital Indonesia”. Acara ini membahas tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dari sisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), manfaat yang ingin dicapai dari pengesahan RUU tersebut, serta pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri teknologi, dan akademisi.Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa pada bulan November mendatang, DPR RI harus memutuskan apakah RUU PDP akan lolos menjadi UU atau tidak. Menurut Farhan, ada sejumlah tantangan dalam proses pengesahan RUU PDP. Persoalan umum yang menjadi perdebatan di DPR RI di antaranya mengenai pengertian data pribadi dan perlindungan data pribadi, serta pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. “RUU ini menempatkan para stakeholder sebagai bagian dari pihak yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi kepentingan konsumen atau data pribadi dari warga negara Indonesia,” tutur Farhan.
Memasuki sesi inti, acara pemaparan materi dibuka dengan pengantar dari moderator. Pada kesempatan ini, Pamungkas menyampaikan bahwa urgensi mengangkat topik workshop berangkat dari faktor historis keberhasilan Indonesia dalam recovery pasca krisis moneter. Dalam hal ini, terdapat tantangan besar terkait keterbatasan anggaran dalam suatu proses perumusan kebijakan. Karenanya, advokasi kebijakan berbasis riset perlu dibudayakan, terutama melalui penyusunan policy brief.

Pada sesi sharing, pemateri pertama menyampaikan bahwa perjalanan sejarah advokasi mengalami pergeseran dari aspek litigasi ke aspek non litigasi. Dalam hal ini, terdapat perluasan paradigma dimana advokasi kini berguna sebagai mekanisme mencari pembelaan bagi kelompok lemah atau rentan. Melengkapi penjelasan sebelumnya, pemateri kedua menyampaikan bahwa policy brief dapat menjadi alternatif dalam upaya mengangkat isu tertentu dalam proses advokasi kebijakan. Dalam hal ini, proses analisis berjalan dalam dua paradigma yaitu politis dan teknokratis. Kendati demikian, proses-proses alternatif dengan mengedepankan basis ilmu pengetahuan, evidence, dan riset dapat menghasilkan output yang lebih tepat sasaran, sehingga perlu diutamakan dalam penyusunan suatu policy brief. (/Mdn)
Mengawali acara workshop, diskusi dibuka dengan sambutan dari Dekan Fisipol UGM, Kaprodi S1 DPP Fisipol UGM, dan Ketua KOMAP Fisipol UGM. Dalam sambutannya, ketiga pembicara menyampaikan bahwa acara ini merupakan inisiatif yang cukup baik dalam mengembangkan proses pembelajaran di masa pandemi. Selain itu, terjadinya pergeseran besar dalam dunia politik, atau dikenal dengan istilah negasif menjadikan berbagai ruang yang ada diisi oleh generasi muda, karenanya diskusi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi para peserta untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai peran masing-masing.
Yogyakarta, 15 Oktober 2021─Social Research Center (SOREC) Fisipol UGM berkolaborasi dengan Departemen Sosiologi menyelenggarakan diskusi daring dengan tajuk “Prekarisasi Pekerja Rentan dan Reformasi Skema Perlindungan Sosial di Masa Pandemi” pada (15/10). Pada kesempatan kali ini, terdapat tiga pemateri diskusi yaitu Indrasari Tjandraningsih, M.A. Dosen Universitas Parahyangan, lalu hadir pula Lajovi Pratama, perwakilan SINDIKASI, dan narasumber terakhir A.B Widyanta M.A. selaku Dosen Departemen Sosiologi UGM. Acara ini diikuti oleh 21 peserta diskusi dan dipandu oleh moderator Rizqyansyah F, Asisten SOREC Fisipol UGM. Secara umum pembahasan dalam diskusi ini mengulik berbagai dinamika para pekerja rentan di masa pandemi dan bagaimana alternatif solusi bagi berbagai permasalahan dalam sistem prekarisasi atau pelemahan. Mengawali sesi pertama, acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan sekretaris SOREC Fisipol UGM, Gregorius Ragil. Dalam sambutannya, Ragil menyampaikan terima kasih atas kehadiran para pemateri dan peserta dalam acara sharing ilmu pengetahuan ini. Selanjutnya, acara ini diharapkan dapat memberikan insight baru yang dapat direfleksikan dan dikontribusikan di masyarakat sesuai peran kita dalam kehidupan sehari-hari.