
Yogyakarta, 14 Juni 2020—Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM mengadakan Ngopi (Ngobrol Minggu Pagi) pada (14/6). Edisi Ngopi pertama ini bertajuk “Disrupsi Informasi dan Pandemi Jelang Pilkada 2020”. Dua narasumber dalam diskusi ini adalah Prof. Dr. Phil. Hermin I Wahyuni, dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM dan Dr. Sri Nuryanti, MA, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ngopi pertama kali ini dimoderatori oleh Novi Kurnia Ph.D, dari S2 Ilmu Komunikasi UGM.
Sri Nuryanti sebagai pembicara pertama membahas mengenai pro kontra dan kerentanan disrupsi informasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Dalam presentasinya, Nuryanti menyebutkan beberapa argumen pro penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, yaitu adanya Kofi Annan Letter of Endorsment yang berisi pemilu masih bisa dilaksanakan di tengah pandemi. Beberapa negara juga berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi, misal Korea Selatan. Pertimbangan lain yaitu teknis pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan tahap-tahapan menuju Pilkada 2020. “Tahapan ini sudah dilakukan dan berhenti karena pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhir,” imbuh Nuryanti.
Nuryanti juga memaparkan beberapa argumen pihak kontra terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Pertama, karena kurva pandemi belum landai dan di beberapa daerah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pembatasan Sosial Berskala Lokal. Argumen kontra lain, yaitu terkait keselamatan penyelenggara, peserta dan pemilih pada Pilkada 2020. Pada Pilkada 2020, KPU juga harus melakukan penyelenggaraan Pilkada dengan baik, tidak hanya terkait dengan intstrumen teknis tetapi juga pemahaman penyelenggaraan yang harus merujuk protokol kesehatan. “Pertimbangan lain jika Pilkada ditunda 2021, KPU mempunyai kesempatan untuk menyiapkan penyelenggaraan lebih baik dan leluasa,” ungkap Nuryanti.
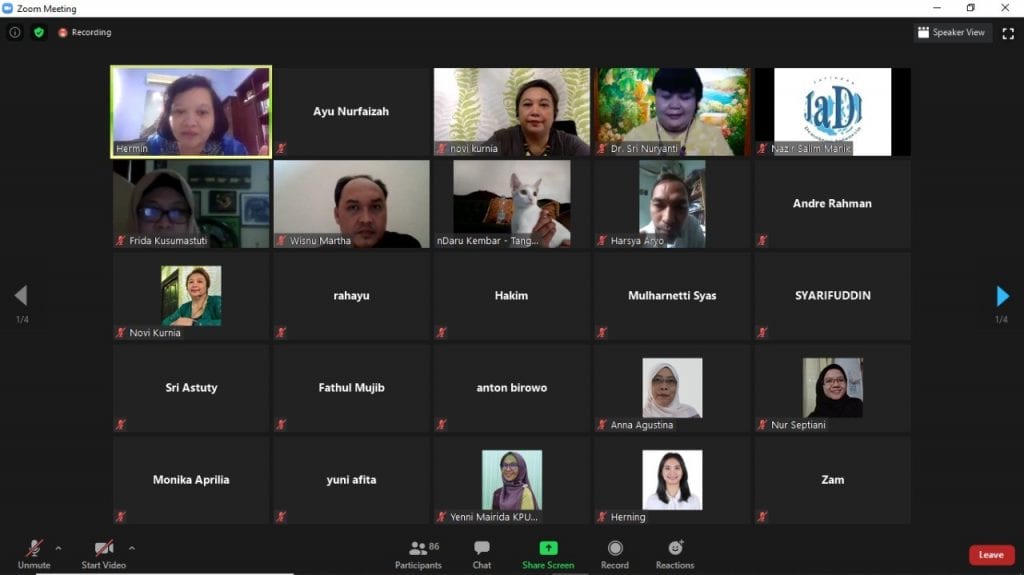
Terkait potensi disrupsi informasi, Nuryanti menyebutkan setidaknya ada tiga jenis potensi jika dilihat dari penyelenggara atau KPU. Pertama, pada penambahan anggaran untuk alat pelindung diri atau protokol kesehatan dan juga potensi disrupsi informasi anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kedua, yaitu potensi terkait tahapan pilkada new normal dan juga pungut hitung yang bisa menjadi sasaran luar biasa disrupsi informasi. Ketiga, yaitu kinerja para penyelenggara yang juga rentan menjadi sasaran disrupsi informasi, hal ini terkait dengan profesionalitas dan integritas penyelenggara Pilkada yang akan datang. “Ketiga potensi disrupsi informasi tersebut, sangat rentan berkembang menjadi hoaks di masyarakat,” tutur Nuryanti.
Hermin melanjutkan diskusi dengan pembahasan seputar komunikasi Pilkada di tengah pandemi dan upaya mengurangi perkembangan hoaks di masyarakat. Baginya, semua elemen masyarakat dapat berperan secara efektif dalam keberhasilan Pilkada. Selain itu juga perlu pendampingan pada masyarakat Indonesia dalam hal pengarusutamaan informasi berbasis pengetahuan. “Perlu dilakukan mainstreaming pada masyarakat Indonesia dalam memberi respon pada informasi yang beredar”, tutur Hermin.
Hal ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kehirukpikukkan dan disrupsi informasi. Hermin menuturkan perlunya mengaktifkan seluruh hubungan dari rantai komunitas yang berpotensi untuk berkontribusi aktif dalam memaknai kehirukpikkan. Rantai komunitas yang dimaksud adalah media massa, jurnalis, akademisi, pegiat literasi, dan lain-lain. “Semua pihak sesuai perannya harus digerakkan untuk melawan hoaks, dengan menggerakkan resonansi masyarakat,” timpal Hermin.
Hermin juga menawarkan alternatif untuk memerangi hoaks pada masyarakat Indonesia. Agenda pertama yang harus dilakukan yaitu memahami karakter masyarakat. Salah satu penelitian kerjasama yang dilakukan Program Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya perempuan cenderung mendiamkan dalam menanggapi hoaks dan ujaran kebencian terkait pemilu. Meskipun begitu ada sekian persen dari masyarakat yang berpotensi untuk memberi wawasan atau meluruskan. “Dari data tadi saya pikir kita bisa memikirkan bersama bagaimana mekanisme prompt corrections yang cocok untuk Indonesia,” sebut Hermin.
Selain memahami karakter masyarakat, Hermin menambahkan perlunya menggerakkan resonansi pada rantai transmisi seperti jurnalis, broadcaster dan orang-orang penting, sebagai agen untuk menangkal hoaks. Rekayasa platform untuk mengurangi hoaks juga mulai dilakukan di Indonesia, misal dengan melambatkan penyebaran informasi di Whatsapp. Contoh-contoh rekayasa platform ini bisa dilihat dari berbagai negara yang sudah cukup berhasil mengurangi kehirukpikukan di media massa. “Meskipun begitu, Indonesia harus menemukan caranya sendiri, karena kita memiliki konteks yang berbeda,” terang Hermin. (/anf)
