
Yogyakarta, 22 Juli 2024─Relasi kuasa NGOs dengan negara, masyarakat akar rumput, donor dan sektor privat telah mengalami perubahan signifikan sejak dua dekade Indonesia paska otoritarian. Demokratisasi yang dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi neo-liberal atau biasa disebut good governance menjadi diskursus dominan yang mengonstruksi identitas pekerja dan institusi NGOs. Merespon realitas tersebut, Social Development Talks yang diselenggarakan Departemen Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (PSdK) Fisipol gelar diskusi bertajuk “Diskursus Politik Kuasa NGO di Indonesia: Tantangan dan Peluang NGO dalam Transformasi Sosial” di Zoom Meeting pada Senin (22/07).
Andreas Budi Widyanto selaku narasumber sekaligus Dosen Sosiologi Fisipol UGM menjelaskan komplikasi yang terjadi dalam pergerakan NGOs sebagai akibat kebijakan good governance. Formasi governmentalitas neoliberal atas NGOs menjadikannya subyek managerial di Indonesia paska otoritarian yang menyebabkan NGOs mengalami difusi atau disebut hybrid organization.
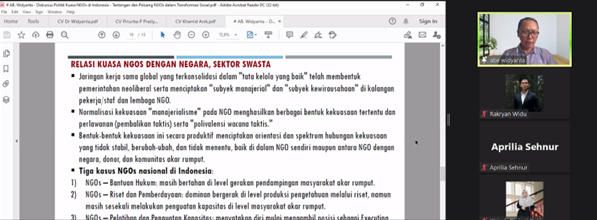
“NGO sebagai subjek managerial dari neoliberal governance dituntut mumpuni mengelola kompleksitas kelembagaan. Mereka harus menyandang tiga peran sekaligus, mulai dari spirit melayani publik, menghidupi dirinya sendiri (fundrising), menyelenggarakan voluntary civil atau pelayanan sosial (CSR),” jelas Andreas.
Berdasarkan laporan CSO Sustainability Index 2023 yang dilakukan oleh Konsil LSM Indonesia menyoroti pada lingkungan hukum dan arus pendanaan yang membatasi gerak NGOs di Indonesia. Undang-undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersempit NGO akibat iklim investasi yang digemborkan pemerintah.
“Perubahan status Indonesia dari lower-middle income menjadi upper-middle income juga berkonsekuensi pada berkurangnya investasi dari lembaga donor ke Indonesia. Begitu pula efek pandemic Covid 2019 lalu,” jelas Anick H.T selaku Direktur Sekretariat Nasional Konsil LSM Indonesia.
Sementara itu, Pinurba Parama Pratiyudha selaku Dosen Departemen PSdK menggarisbawahi spirit dari NGO sebagai gerakan organic dan berbasis voluntarism. Menurutnya, iklim NGOs saat ini memunculkan pertanyaan sejauh mana voluntarism sebagai hakikat NGO itu hadir.
“Realitanya saat ini voluntarism yang terlihat justru dibingungan oleh keberlajutan lembaga, kesejahteraan diri, dan memunculkan pragmatism karena (NGO) mulai melihat jenjang karir dan sebagainya,” jelas Pinurba.
Pergerakan NGOs yang dituntut masuk dalam gelombang neoliberalistik namun pada praktiknya memiiki mindset welfare-state. Hal ini merujuk pada Preambule Undang-Undang Dasar yang mengklaim Indonesia sebagai welfare-state namun praktik hidup aktor-aktornya justru kapitalistik. Uniknya, kompleksitas ini memunculkan bentuk baru dari NGO yang berangkat dari komunitas dan gerakan konstribusi masyarakat dengan spirit dan concern yang sama, misalnya Pandawara (Kelompok penggerak berfokus pada permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan).
“Untuk meruntuhkan tembok penghambat ini, perlu mempertemukan tiga hal, yaitu dari kebijakan, kerjasama NGO dan pemerintah dalam swakelola, serta kesiapan OMS yang eligible,” tukas Anick.
Adapun kegiatan diskusi ini sebagai bentuk dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Keberlanjutan poin 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh serta poin 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan (/dt)
