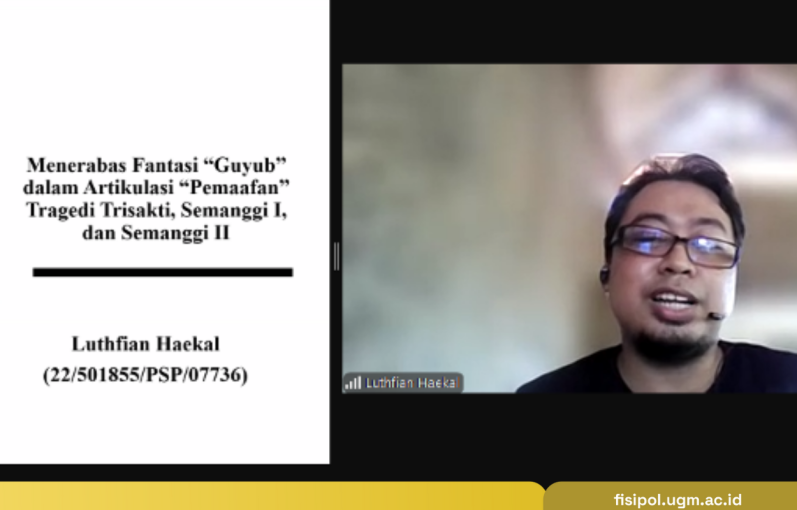
Yogyakarta, 12 November 2024 – Diseminasi hibah riset dalam acara “Research Week 2024” oleh salah satu mahasiswa S2 Departemen Politik Pemerintahan mengangkat isu political forgiveness dalam kasus tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Riset ini merupakan hasil karya Luthfian Haekal yang menyoroti artikulasi “pemaafan” negara terhadap keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi. Kemudian, riset ini menggunakan strategi analisis fenomenologi hermeneutik dan pengumpulan data menggunakan wawancara dengan keluarga korban, tim relawan, YLBHI, IKOHI, pengawalan kebijakan penyelesaian non-yudisial, salah satu purnawirawan militer, dan Tim PPHAM dan PKP HAM; observasi; dan kajian pustaka.
Riset ini mengembalikan diskursus penyelesaian kasus HAM berat melalui upaya mekanisme non-yudisial. Peranan negara dalam memenuhi hak korban dibingkai dalam fantasi ‘“guyub” yang menempatkan negara dapat membawa kebaikan bagi seluruh warga. Terlebih, mekanisme non-yudisial disebut sebagai bentuk penghargaan terhadap HAM dan wujud rekonsiliasi dalam menjaga persatuan nasional.
Dalam temuan riset ini, juga melacak sejumlah indikasi-indikasi “pemaafan” dalam upaya memulihkan hak korban. Dalam aspek kewarganegaraan, negara memungkinkan korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat menjadi “warga negara Indonesia” kembali. Kedua, dalam aspek ekonomi dengan diberikannya pelatihan ketenagakerjaan, kesempatan kerja di BUMN, pemanfaatan CSR BUMN. Ketiga, dari aspek materiil lain, diberikan bantuan tempat ibadah, jaminan hari tua, BPJS paling tinggi, bantuan/rehabilitasi sosial, pembangunan infrastruktur tertentu, hingga sejumlah bantuan pertanian. Empat, dari segi pendidikan juga diberikan beasiswa LPDP afirmasi. Hingga dari aspek pencegahan juga diberikan layanan bantuan sarana prasana dan keamanan ketertiban serta pendidikan HAM.
“…relasi transaksional terjadi untuk menggantikan duka dengan seperangkat ‘hak-hak yang tertunda’ – kewarganegaraan, ekonomi, materiil lain, pendidikan, pencegahan, segala macam itu dibayangkan sebagai ‘hak-hak tertunda’ yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya,” ungkap Luthfian.
Pada saat yang sama, riset ini juga memberikan catatan penting dua artikulasi yang membayangi fiksi kenegaraan. Pertama, menyoal keadilan, negara lebih memprioritaskan mekanisme non-yudisial meskipun negara juga tidak serta merta mengabaikan yudisial, akan tetapi Ibu Sumarsih selaku salah satu keluarga korban menuntut adanya mekanisme yudisial karena terdapat kekhawatiran yang berakhir pada impunitas. Kedua, fragmen memoria, ditunjukkan untuk menghadirkan kembali korban melalui simbolisasi tertentu dalam merawat ingatan untuk menjumpai keadilan, seperti melalui coretan, kaos, atribut motor, dsb.
“Pelampauan dalam kategori kehadiran, penerabasan fantasi memungkinkan kita untuk melampaui kategori kehadiran soal ada. Ada tidak selalu final dan tidak selalu total, dia selalu parsial. Dan itu membuka jalan perlawanan juga,” tutur Luthfian.
